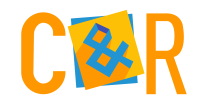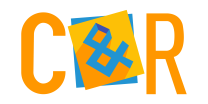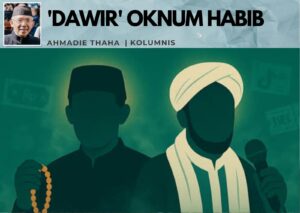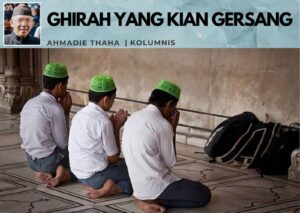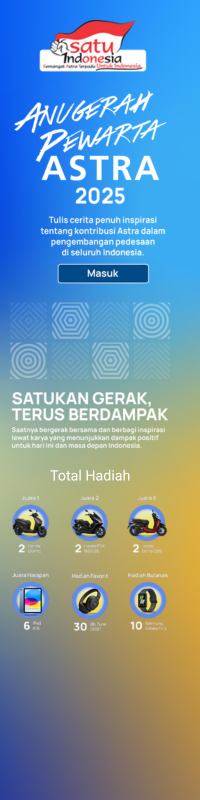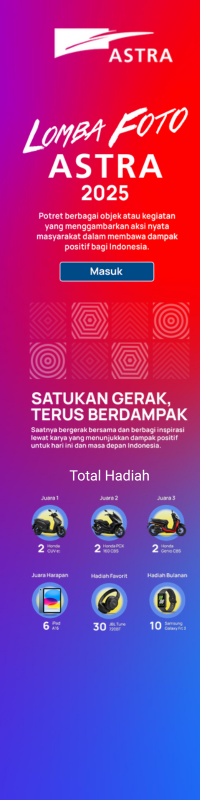Ketika hukum digunakan sebagai arena tarik-menarik kekuatan politik, maka putusan hukum pun menjadi bias dan kehilangan independensinya.
Oleh: Chappy Hakim
Ceknricek.com–Dalam sistem hukum Indonesia, presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan abolisi dan amnesti. Keduanya adalah instrumen hukum yang diakui dalam konstitusi.
Abolisi berarti penghentian proses hukum pidana sebelum ada keputusan pengadilan, sedangkan amnesti adalah penghapusan pidana secara menyeluruh, sering kali diberikan dalam kerangka rekonsiliasi nasional atau politik.
Namun ketika kedua instrumen itu digunakan tanpa transparansi, dan bahkan cenderung diam-diam untuk menyelamatkan elite politik, maka legitimasi hukum itu sendiri dipertaruhkan.
Kasus terbaru yang menyita perhatian adalah dugaan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, serta amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
Nama Tom Lembong dikenal sebagai sosok teknokrat yang pernah menjabat sebagai Kepala BKPM dan Menteri Perdagangan. Ia juga dikenal sebagai figur independen yang kritis terhadap beberapa kebijakan strategis pemerintahan.
Sementara Hasto Kristiyanto adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, partai penguasa yang sangat sentral dalam konfigurasi politik nasional saat ini.
Publik bertanya-tanya, apa sebenarnya perkara yang menjerat kedua tokoh tersebut hingga perlu diberikan abolisi dan amnesti? Tidak ada keterangan resmi yang terbuka kepada masyarakat, tidak ada transparansi prosedural, dan bahkan tidak ada pernyataan hukum yang lengkap yang menjelaskan alasan pemberian pengampunan tersebut. Justru yang muncul ke permukaan adalah spekulasi bahwa kedua tindakan itu sarat dengan motif politik.
Dalam kasus Tom Lembong, dugaan bahwa dirinya akan menghadapi proses hukum akibat kebijakan investasi di masa lalu justru berakhir dengan keputusan penghentian melalui abolisi. Jika proses hukum belum dijalankan secara terbuka dan pengadilan belum bekerja, maka abolisi justru memperlihatkan intervensi kekuasaan yang mengaburkan keadilan.
Lebih jauh, jika seseorang seperti Lembong, yang dikenal profesional dan tidak dekat dengan pusat kekuasaan saat ini, mendapat abolisi, maka muncul dugaan bahwa keputusan tersebut adalah bagian dari strategi kompromi politik tingkat tinggi.
Sementara itu, kasus Haasto Kristiyanto menunjukkan pola yang berbeda, tetapi tetap berada dalam logika kekuasaan yang sama. Sebagai petinggi partai politik besar, Hasto memiliki posisi vital dalam stabilitas internal partai maupun relasi dengan kekuasaan eksekutif.
Amnesti yang diberikan kepadanya diduga terkait pernyataan-pernyataan atau tindakan politik yang bisa menjeratnya ke dalam perkara hukum. Di sinilah problem etis dan yuridis muncul: apakah amnesti ini diberikan karena alasan objektif demi kepentingan nasional, atau justru sebagai mekanisme pelindung bagi aktor politik yang punya akses langsung ke jantung kekuasaan?
Dalam konteks teori politik hukum, fenomena ini bisa dijelaskan melalui pendekatan instrumentalisme hukum. Hukum bukan lagi berdiri netral sebagai penjaga keadilan, melainkan menjadi alat politik untuk menyelamatkan kawan dan menghukum lawan.
Ketika proses hukum hanya diberlakukan kepada mereka yang lemah, dan dihentikan bagi mereka yang punya akses politik, maka yang terjadi bukanlah negara hukum, melainkan negara kekuasaan.
Pemberian abolisi dan amnesti tanpa transparansi juga memperkuat asumsi adanya praktik state capture ketika institusi negara tidak lagi melayani kepentingan publik, tetapi dibajak oleh kepentingan segelintir elite.
Dalam kerangka ini, tindakan pengampunan bukan lagi mekanisme hukum yang mulia, tetapi justru cermin dari krisis keadilan di republik ini. Siapa yang salah dalam semua ini? Tentu bukan hanya individu seperti Tom Lembong atau Hasto Kristiyanto. Mereka bisa saja hanyalah figur yang terjebak dalam tarik-menarik kekuasaan.
Yang patut dipersoalkan adalah bagaimana institusi-institusi negara, termasuk Presiden sebagai pemegang hak prerogatif, mengambil keputusan yang sangat strategis tanpa proses yang akuntabel. Di balik itu, terdapat aktor-aktor lain baik partai politik, penasihat hukum, maupun kelompok kepentingan yang bermain dalam senyap.
Dalam semua kisah ini, sutradara utamanya adalah sistem kekuasaan itu sendiri. Sebuah sistem yang belum selesai membangun mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan yang luar biasa besar.
Sebuah sistem yang membiarkan hukum tunduk kepada kepentingan, bukan pada kebenaran. Sudah saatnya publik menuntut transparansi atas setiap bentuk pengampunan hukum yang diberikan negara.
Abolisi dan amnesti bukanlah privilege untuk segelintir orang dekat kekuasaan. Keduanya adalah mekanisme hukum yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepentingan publik. Jika tidak, maka hukum akan terus menjadi panggung sandiwara, dan keadilan hanyalah ilusi yang terus dijauhkan dari rakyat.
Ke depan, bangsa ini harus memperkuat komitmen bahwa hukum tidak boleh lagi dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan atau mengamankan kepentingan politik jangka pendek.
Hukum harus berdiri di atas seluruh warga negara tanpa membedakan jabatan, kedekatan dengan kekuasaan, atau latar belakang partai. Mekanisme pengampunan seperti abolisi dan amnesti harus dikembalikan pada hakikatnya sebagai sarana keadilan restoratif yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Masyarakat sipil, media independen, dan lembaga pengawasan seperti Komnas HAM dan KPK harus diperkuat peranannya dalam mengawasi penggunaan hak prerogatif negara.
Pemerintah dan parlemen juga perlu merevisi kerangka hukum yang mengatur pemberian abolisi dan amnesti agar tidak bisa lagi digunakan secara sepihak dan tertutup. Diperlukan mekanisme konsultatif dan prosedur keterbukaan informasi agar publik dapat menilai alasan pemberian pengampunan secara objektif.
Hanya dengan cara itulah hukum dapat kembali menjadi fondasi keadilan dan demokrasi, bukan sekadar alat kosmetik kekuasaan. Sebab jika hukum terus diperalat, maka kepercayaan rakyat terhadap negara akan runtuh, dan demokrasi yang dibangun dengan susah payah sejak reformasi hanya akan tinggal nama.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan besar proses hukum yang membayangi Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto sejak awal memang sarat dengan nuansa politik. Tuduhan-tuduhan yang muncul terhadap keduanya diduga bukan semata-mata berdasar pada pelanggaran hukum yang murni, melainkan juga akibat dari friksi kekuasaan, persaingan kepentingan antar faksi politik, serta dinamika internal elite penguasa.
Dalam konteks ini, langkah pemberian abolisi dan amnesti terhadap mereka bisa saja bukan ditujukan untuk menegakkan keadilan, melainkan sebagai strategi penyelesaian politik untuk meredam konflik yang lebih besar atau menjaga stabilitas kekuasaan jelang momen-momen elektoral.
Ketika hukum digunakan sebagai arena tarik-menarik kekuatan politik, maka putusan hukum pun menjadi bias dan kehilangan independensinya.
Jakarta 1 Agustus 2025