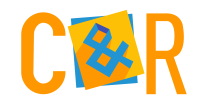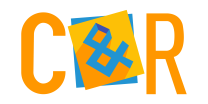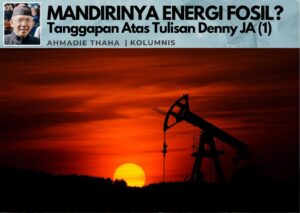Di negeri ini, sesuatu yang dulu sederhana, biasa biasa saja kini terasa ”menakutkan”.
Oleh: Chappy Hakim
Ceknricek.com–Di negeri ini, sesuatu yang dulu sederhana, biasa biasa saja kini terasa ”menakutkan”. Menyanyi bisa dianggap melanggar hukum. Punya rumah tua dianggap kaya. Rekening bank yang tidak aktif terancam disita negara. Negara yang seharusnya menjadi pelindung, perlahan-lahan justru tampak hadir seolah-olah sebagai sosok penagih, pengawas, bahkan ”pemeras”. Hidup di Indonesia, dari hari ke hari, seolah makin kehilangan rasa aman yang seharusnya diberikan oleh negara kepada rakyatnya.
Semua bermula dari semangat hukum yang katanya untuk keadilan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral dan ekonomi para pencipta lagu. Tetapi dalam praktiknya, terjadi distorsi niat. Lagu-lagu yang diputar di warung kopi, acara ulang tahun anak, atau sekadar dinyanyikan di panggung kampung, kini dikhawatirkan bisa dikenai royalti. Orang jadi takut menyanyi, karena bayang-bayang akan dikenai denda.
Para pelaku UMKM pun ikut cemas. Tanpa edukasi yang memadai, mereka tiba-tiba menerima surat tagihan royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Banyak yang tidak tahu harus membayar untuk apa, dan bagaimana uang itu akan disalurkan. Lebih parah lagi, banyak pencipta lagu sendiri bahkan tidak tahu berapa royalti yang terkumpul atas nama mereka. Transparansi yang minim, sosialisasi yang buruk, dan pendekatan yang cenderung memaksa, membuat hukum kehilangan keadilan sosialnya.
Ahli hukum UI, Dr. Edmon Makarim, pernah mengingatkan bahwa tidak semua pemutaran lagu harus dikenakan royalti. “Hukum hak cipta bukan untuk menakut-nakuti orang yang hanya ingin bernyanyi di warung kopi atau acara keluarga,” ujarnya dalam sebuah forum.
Pengamat budaya Hikmat Darmawan juga mengkritik pendekatan hukum yang terlalu sempit dalam memahami ruang publik.
“Kalau semua tempat di luar kamar tidur dianggap ruang publik, kita sedang menuju masyarakat paranoid secara budaya.”
Musisi legendaris Iwan Fals bahkan menyatakan keprihatinannya secara terbuka. “Kalau semua harus bayar untuk sekadar nyanyi, nanti rakyat jadi takut. Lagu itu seharusnya mempertemukan hati, bukan memisahkan dompet.”
Ini bukan hanya suara musisi, tapi suara nurani bangsa yang merasa nilai-nilai hidup mulai direduksi menjadi angka-angka transaksional. Celakanya, itu bukan satu-satunya isu. Konon di Pati, Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang drastis juga menghantui warga. Banyak rumah warisan orang tua yang dulu dianggap biasa- biasa saja, kini dikenai pajak setinggi properti mewah.
Nilai NJOP dinaikkan sepihak oleh pemerintah daerah, tanpa dialog, tanpa analisis sosial, dan tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat. Warga di kampung-kampung kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, tiba-tiba khawatir harus membayar pajak yang beberapa kali lipat lebih mahal dibanding tahun lalu. Rumah bukan lagi tempat tinggal, tapi dianggap alat produksi yang harus dipajaki habis-habisan.
Tak berhenti di situ, kini muncul lagi aturan baru: rekening pasif akan disita negara. Bank Indonesia dan OJK menyatakan akan menerapkan kebijakan penyitaan terhadap rekening bank yang tidak aktif selama setahun dan tidak ada transaksi minimal. Alasannya: efisiensi dan pencegahan kejahatan finansial. Tapi kebijakan ini membuat banyak orang bertanya, bagaimana dengan rekening pensiunan? Bagaimana dengan tabungan kecil untuk anak-anak? Bagaimana jika uang itu memang sengaja disimpan untuk kebutuhan darurat?
Bukannya memperkuat rasa aman finansial, negara justru menciptakan ketidakpastian baru. Rakyat makin merasa tak punya ruang privat. Harta kecil pun tak lagi aman. Rekening yang dulu disimpan untuk berjaga-jaga kini bisa dianggap “tidur” dan terancam dirampas. Bukan oleh maling, tapi oleh sistem. Di tengah gempuran pungutan dan ancaman ini, rakyat seolah dituntut untuk patuh tanpa boleh bertanya. Padahal, mereka bukan anti hukum. Mereka hanya ingin negara berlaku adil, manusiawi, dan memberi kejelasan. Bukan menumpuk aturan yang membuat hidup makin ruwet, tapi menghadirkan ketenangan lewat kepastian.
Apa yang bisa dilakukan? Pertama, negara harus membedakan antara pendekatan hukum dan pendekatan manusia. Sosialisasi royalti musik, misalnya, harus dilakukan dengan partisipatif. Jelaskan dengan sederhana, beri klasifikasi antara usaha besar dan usaha kecil. Beri ruang kepada masyarakat untuk bertanya, bukan langsung disodori surat tagihan.
Kedua, sistem manajemen royalti harus dibuka seluas- luasnya. Pencipta lagu harus tahu siapa yang memutar lagunya, berapa yang dibayarkan, dan ke mana larinya uang royalti. Jangan sampai sistem ini hanya jadi “pabrik uang” bagi segelintir orang di balik lembaga kolektif.
Ketiga, soal pajak dan rekening rakyat, harus ada kebijakan afirmatif. PBB perlu mempertimbangkan kondisi sosial pemilik rumah, bukan semata NJOP. Rekening nganggur bukan berarti tidak berguna. Mungkin itu milik kakek di desa yang disimpan untuk biaya cucunya masuk sekolah.
Negara yang benar-benar berpihak pada rakyat adalah negara yang tahu bedanya pengawasan dan intimidasi. Negara yang tahu kapan menegakkan hukum, dan kapan menyentuh dengan hati. Jika hukum hanya digunakan sebagai alat tagih dan hukum hanya hadir ketika rakyat harus membayar, maka itu bukan negara hukum.
Musik, rumah, dan tabungan adalah tiga hal yang seharusnya memberi rasa aman dan bahagia. Tapi kini, ketiganya justru membuat rakyat gelisah. Jika terus begini, bukan hanya suara nyanyian yang hilang dari negeri ini, tapi juga suara tawa, rasa tenteram, dan kepercayaan kepada negara. Disisi lain luas beredar tentang para elit yang tertangkap korupsi trilyunan rupiah hanya di hukum ringan bahkan ada yang lolos dari tuntutan hukum
Catatan Penutup.
Tulisan ini adalah seruan agar negara hadir tidak sekadar dengan peraturan, tetapi juga dengan perasaan. Agar hukum tidak hanya tajam ke rakyat kecil, tetapi juga adil kepada semua. Dan agar Indonesia tak kehilangan jiwa sosialnya hanya demi mengejar setoran kas negara. Karena rakyat sejatinya bukanlah sebuah mesin ATM.
Referensi
- UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta
- Kompas.com, CNN Indonesia, Tempo (2021–2025): soal royalti lagu, kenaikan PBB, dan penyitaan rekening
- Wawancara publik: Edmon Makarim (UI), Hikmat Darmawan, Iwan Fals