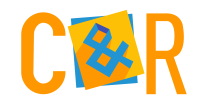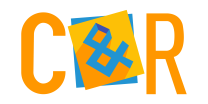Walhasil, di tengah dunia yang dipenuhi noise — secara literal dan emosional — anak-anak justru menunjukkan bahwa mereka bisa menangkap makna lewat irama.
Oleh: Ahmadie Thaha
Ceknricek.com– “Katanya musik itu bahasa universal. Tapi siapa sangka, dalam kasus anak-anak zaman now, musik bukan cuma bahasa — dialah guru emosi, terapis gratis, bahkan kadang lebih jujur dari wajah ibunya sendiri.”
Bayangkan ini: seorang bocah tiga tahun sedang duduk di lantai ruang tamu, menggigit marshmallow dengan khidmat, sementara di latar belakang mengalun lagu melankolis Beethoven. Tiba-tiba, wajahnya cemberut. Bukan karena buah habis — tapi karena musik itu sedih.
Apakah anak ini sudah paham apa itu kesedihan? Ilmuwan dari University of Pennsylvania bilang: “Yes, absolutely, even toddlers feel the blues — via music.”
Bahkan, mereka menemukan bahwa anak usia 3 hingga 5 tahun sudah bisa membedakan musik bahagia, sedih, takut, dan tenang — bahkan ketika mereka sendiri masih mengucapkan “rr” jadi “glurgh”.
Dua studi besar, dari University of Pennsylvania dan Durham University, membawa kabar mengejutkan: anak-anak, bahkan balita, ternyata bisa mengenali emosi lebih baik lewat musik daripada wajah manusia. Apalagi wajah kita yang sedang stres memikirkan cicilan KPR.
Fakta pertama: Musik lebih jelas dari wajah. Menurut studi Durham, ketika anak diminta mengenali emosi dari tubuh manusia (dengan wajah sengaja diburamkan) sambil mendengar musik yang tidak cocok, akurasi mereka menurun drastis.
Bayangkan: tubuh menunjukkan ketakutan, tapi musiknya malah seperti soundtrack kartun Spongebob. Otak anak pun berkata, “Ah, ini pasti lucu-lucuan aja.”
Fakta kedua: Emosi tinggi, akurasi pun tinggi. Penelitian dari Penn menunjukkan bahwa emosi high-arousal seperti senang dan takut dikenali lebih akurat daripada emosi low-key macam sedih dan tenang.
Artinya, musik yang menggelegar lebih mudah dimengerti dibanding musik yang pelan dan mellow. Ya, seperti kita semua, rupanya anak-anak juga lebih paham teriakan dibanding bisikan.
Nah, jika Anda orangtua yang selama ini mengandalkan wajah penuh khawatir, senyuman palsu, atau tatapan tajam untuk “mengajarkan” emosi pada anak — mungkin sudah saatnya Anda outsource ke Spotify.
Kenapa repot-repot mencemaskan kemampuan ekspresif Anda, kalau ternyata anak-anak lebih percaya pada dentingan piano, petikan gitar, atau efek string film Disney?
Mungkin di masa depan, kita akan menyekolahkan anak-anak ke Akademi Emosi Musikalis — bukan PAUD biasa — di mana anak tidak diajarkan alfabet, tapi disetelkan Chopin saat sedih, dan Skrillex saat hiperaktif.
Penelitian Penn juga menunjukkan bahwa anak-anak dengan kecenderungan callous-unemotional (alias datar, tak bersalah, dan mirip villain film) kesulitan mengenali emosi dari musik — kecuali ketakutan. Ya, mereka tetap bisa membedakan musik menakutkan.
Apakah ini berarti bahwa satu-satunya jalan untuk menyentuh hati anak yang “dingin” adalah lewat lagu atau film horor? Atau mungkin kita butuh versi “Therapy through Thriller” sebagai metode intervensi?
Ilmu menyarankan: ya. Musik bisa menjadi pintu masuk alternatif untuk memahami emosi bagi mereka yang tak responsif pada ekspresi wajah atau sentuhan sosial. Ini sangat masuk akal, mengingat wajah manusia sekarang lebih sering dilihat di bentuk emoji, bukan langsung.
Jika musik kini terbukti lebih efektif sebagai socialization agent, maka mungkin kita harus akui bahwa baby shark, frozen, tiktok beat telah mengambil alih fungsi komunikasi emosional yang dulu dipegang oleh keluarga, guru, dan masyarakat.
Anak-anak generasi Alpha dan Betha yang lahir tahun ini ternyata: Belajar empati dari soundtrack Pixar,, mengenal ketakutan lewat jump scare audio YouTube, merasa gembira karena beat viral. Bahkan menangis bukan karena dimarahi, tapi karena lagunya “Lofi Sad Piano 10 Hours”.
Sungguh ironis, bahwa di dunia yang makin visual — kita justru kembali ke pendengaran sebagai jalur utama afeksi. Coba tes kecerdasan anak-anak dengan asesmen Multiple Intelligence, Anda akan lebih tahu siapa diri mereka.
Jadi, haruskah kita sering memainkan lagu untuk mendidik anak? Jawabannya: Ya, tapi dengan akal sehat dan konteks.
Pertama, gunakan musik sebagai jembatan afeksi, bukan pelarian. Mainkan musik yang sesuai dengan suasana hati yang ingin dibentuk. Musik bisa membantu, bukan menggantikan, komunikasi emosional.
Kedua, sadari bahwa anak-anak mendengar lebih baik daripada melihat. Jadi ketimbang memasang wajah pura-pura sabar, cobalah nyanyikan perasaan Anda.
Ketiga, buatlah kurikulum emosi berbasis audio. Guru TK tak perlu lagi menggambar wajah sedih — cukup bawa speaker, lalu putar cuplikan lagu violin bernada sedih.
Keempat, evaluasi ulang peran media dan musik pop dalam membentuk afeksi anak. Jangan sampai mereka lebih paham rasa patah hati dari lagu galau TikTok, dibanding kisah nyata dalam hidup.
Walhasil, di tengah dunia yang dipenuhi noise — secara literal dan emosional — anak-anak justru menunjukkan bahwa mereka bisa menangkap makna lewat irama.
Dunia dewasa bisa belajar dari temuan hasil penelitian itu. Mungkin saatnya kita juga berhenti melihat dunia dengan prasangka, dan mulai mendengarkannya dengan hati.
Atau kalau tidak bisa, ya minimal, jangan ganggu anak mendengar musiknya. Karena barangkali, di balik ketukan drum digital itu, tersembunyi pelajaran tentang ketakutan, cinta, dan kemanusiaan yang lebih dalam dari semua seminar parenting gabut.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 11/8/2025
Referensi:
– Paz, Y. et al. (2025). “Hearing a Feeling: Music Emotion Recognition and Callous‐Unemotional Traits in Early Childhood.” Child Development.
– Ross, P. et al. (2023). “Emotional Music Bursts and Auditory Dominance in Children”. Journal of Experimental Child Psychology.
–