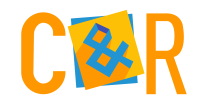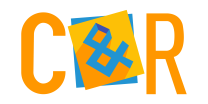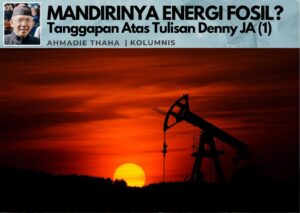Di dunia yang penuh keramaian ini, ketenangan bukanlah barang langka. Ia ada, ia nyata di dalam diri kita sendiri, menunggu untuk ditemukan.
Oleh: Chappy Hakim
Ceknricek.com–Manusia sepanjang hidupnya akan selalu bergulat dengan pertanyaan yang tampak sederhana, namun sesungguhnya sangat mendasar: “Aku ini datang dari mana, dan akan ke mana setelah mati?” Pertanyaan itulah yang sering kali menjadi sumber kegelisahan yang paling sunyi, yang tak bisa dijawab hanya dengan pengetahuan teknis atau pencapaian duniawi. Kegelisahan ini muncul bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena kehampaan makna yang menyelinap di balik keramaian hidup sehari-hari.
Dari sanalah agama lahir. Agama hadir sebagai upaya besar umat manusia untuk menjawab kegelisahan itu. Dengan menawarkan narasi penciptaan, tujuan hidup, dan kehidupan setelah mati, agama memberikan semacam “peta” dalam menjalani dunia yang tak pasti ini. Namun yang ironis, tidak sedikit orang yang justru makin gelisah ketika mendalami agama. Bukan karena agamanya, tetapi karena cara agama itu diajarkan. Terlalu banyak “ancaman” yang disodorkan, terlalu banyak hitam-putih antara dosa dan pahala, terlalu sering surga dan neraka digunakan sebagai alat tekanan. Bukannya tenang, jiwa manusia malah diburu oleh rasa takut, takut salah, takut tidak cukup suci, takut tidak diterima oleh Tuhan yang digambarkan sangat murka.
Di tengah situasi seperti itu, banyak yang kemudian bertanya ulang: benarkah ketenangan bisa ditemukan lewat jalan agama yang dipenuhi oleh dogma dan ancaman? Ataukah ada jalan lain yang lebih bersifat personal, lebih jujur, dan lebih damai? Dalam menjawab itu, kita bisa menengok kembali para pemikir besar dari berbagai zaman dan belahan dunia, yang sejak lama telah merenungkan arti hidup dan ketenangan.
Salah satunya adalah Epictetus, filsuf Stoik dari Yunani kuno. Baginya, ketenangan hidup terletak pada kemampuan membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Ia berkata, “Bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi cara kita memandang peristiwa itu.” Pikiran kitalah yang membuat sesuatu tampak menakutkan atau menenangkan. Maka, jika ingin hidup damai, kendalikan pikiran sendiri, bukan mencoba mengatur dunia luar yang memang tak bisa kita kuasai sepenuhnya. Dalam ajaran Stoik, kedamaian adalah hasil dari penerimaan, bukan penolakan terhadap kenyataan.
Dari Timur, ajaran Buddha menyumbangkan cara pandang yang sama menyejukkan. Menurut Sang Buddha, akar penderitaan manusia adalah tanha, keinginan, nafsu, dan keterikatan. Ketika manusia terlalu melekat pada sesuatu, entah harta, status, atau bahkan identitas diri, ia akan mudah gelisah saat kehilangan semua itu. Jalan menuju ketenangan bukanlah menambah apa yang dimiliki, melainkan melepaskan apa yang tidak perlu. Dalam empat kebenaran mulia dan jalan berunsur delapan, Buddha menunjukkan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang ajaib, tapi bisa dipelajari dan dilatih lewat kesadaran penuh, disiplin batin, dan welas asih.
Lalu ada Søren Kierkegaard, pemikir eksistensialis dari Denmark, yang melihat kegelisahan sebagai bagian tak terelakkan dari kehidupan manusia. Baginya, manusia adalah makhluk yang sadar akan kebebasan, dan karena itu justru merasa takut. Takut salah memilih, takut hidup sia-sia, takut mati tanpa makna. Kierkegaard menyarankan agar manusia berani melompat dalam iman, bukan iman buta, melainkan keputusan pribadi untuk hidup otentik dan bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya sendiri. Dalam sikap inilah muncul ketenangan: bukan dari jawaban pasti, melainkan dari keberanian untuk hidup dengan pertanyaan.
Demikian pula Jalaluddin Rumi, penyair sufi besar dari Persia yang menggubah ribuan bait puisi cinta kepada Tuhan. Rumi tidak melihat Tuhan sebagai sosok menakutkan, tetapi sebagai kekasih yang selalu merindukan kita. “Tuhan bukan marah padamu,” tulis Rumi, “Tuhan merindukanmu.” Dalam puisinya, ia menggambarkan manusia seperti seruling bambu yang menangis karena terpisah dari rumpunnya simbol dari jiwa yang rindu pulang pada asalnya. Bagi Rumi, ketenangan sejati hanya akan ditemukan ketika cinta telah menggantikan rasa takut, dan ketika kehadiran Tuhan dirasakan bukan sebagai hakim, melainkan pelukan.
Pemikiran Rumi menembus sekat agama dan budaya. Ia memahami bahwa penderitaan manusia bukan karena kurang ajar pada Tuhan, melainkan karena lupa akan hakikat dirinya. Dalam Mathnawi dan Diwan-e Shams-e Tabrizi, ia mengajak manusia untuk berhenti mencari Tuhan di luar, dan mulai menengok ke dalam. “Apa yang kamu cari, sedang mencari kamu juga,” katanya. Ketenangan bukan ditemukan dengan melarikan diri dari kehidupan, tetapi dengan menghadapi kehidupan sepenuhnya, dan melihat bahwa di balik gejolak dunia, ada samudra cinta yang tak pernah kering.
Rumi juga mengajarkan bahwa luka bukan hal yang harus disesali, tetapi justru pintu masuk bagi pencerahan. “Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu.” Ketika manusia berhenti memusuhi rasa sakit, dan mulai mendengarkannya, saat itulah ketenangan pelan-pelan menyusup ke dalam jiwa. Rumi tak pernah meminta kita untuk sempurna, ia hanya mengajak kita untuk jujur: kepada diri sendiri, kepada Tuhan, dan kepada hidup itu sendiri.
Kembali pada pertanyaan awal yaitu bagaimana cara menemukan ketenangan dalam dunia yang penuh kegelisahan ini?
Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa ketenangan bukanlah hasil dari situasi yang ideal, melainkan dari cara kita bersikap terhadap situasi itu. Ia bukan sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang dibangun. Seperti kata Carl Jung, “Siapa yang melihat ke luar akan bermimpi, siapa yang melihat ke dalam akan terbangun.” Ketenangan adalah proses sadar yang dimulai dari mengenali luka batin, menerima ketidaksempurnaan, dan berhenti mencari pembenaran dari luar.
Kedua, kita perlu belajar melepaskan. Banyak orang hidup gelisah karena ingin segala sesuatu berjalan sesuai harapan. Padahal, hidup tidak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Dalam dunia yang bergerak liar, satu-satunya kendali yang nyata adalah kendali atas respons kita. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan merelakan apa yang memang bukan milik kita. Di situlah ada ruang untuk damai.
Ketiga, berdamailah dengan ketidaktahuan. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mati. Tapi bukankah justru karena hidup ini sementara, ia menjadi berharga? Seperti yang ditulis Albert Camus dalam The Myth of Sisyphus, kita bisa memilih untuk tetap tersenyum di tengah absurditas hidup. Hidup tidak selalu harus dimengerti, cukup dijalani dengan sepenuh hati.
Akhirnya, ketenangan adalah keputusan. Keputusan untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi dalam kesadaran. Keputusan untuk tidak lagi mencari jawaban pasti, tapi hidup dengan pertanyaan secara jujur. Keputusan untuk mencintai hidup apa adanya, lengkap dengan luka, tawa, kehilangan, dan harapan.
Di dunia yang penuh keramaian ini, ketenangan bukanlah barang langka. Ia ada, ia nyata di dalam diri kita sendiri, menunggu untuk ditemukan.
Catatan Referensi Untuk pendalaman:
- Epictetus, The Enchiridion
- Gautama Buddha, Dhammapada
- Søren Kierkegaard, The Sickness Unto Death
- Rumi, The Essential Rumi, trans. Coleman Barks
- Carl Jung, Modern Man in Search of a Soul
- Thich Nhat Hanh, Peace Is Every Step
- Albert Camus, The Myth of Sisyphus
Jakarta 6 Agustus 2025
Chappy Hakim