Ceknricek.com -- Konflik PPP dengan NU mencapai klimaksnya pada saat rezim Orde Baru berencana menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan organisasi massa. NU menerima asas tunggal, setelah itu menyatakan sikap berpisah dengan PPP dan kembali ke khittah 1926.
Duka tragedi Tanjung Priok belum lagi kering ketika K.H. Abdurahman Wahid atau Gus Dur berakrab-akrab dengan Panglima ABRI, Jenderal Benny Moerdani. Pada November 1984, sebulan setelah tragedi Priok, Gus Dur menemani Benny Moerdani ke Lirboyo Kediri. Di pesantren yang dipimpin Kiai Machrus Ali mereka disambut sekitar 800 ulama--termasuk Kiai As’ad Syamsul Arifin, sesepuh berpengaruh di kalangan nahdliyin saat itu. Dari sini, safari dilanjutkan ke pesantren lainnya di Jawa Timur.

Sumber: NU Online
Aminudin dalam buku Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto (1999) menerjemahkan langkah Gus Dur itu sebagai bagian dari usahanya untuk melenyapkan citra radikalisme umat Islam, terutama NU, di mata rezim Orde Baru.
Tragedi Tanjung Priok menewaskan pulusan orang dan sampai sekarang petinggi yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa ini tidak diadili. Benny adalah salah satu petinggi yang dianggap bertanggung jawab itu.

Tanjung Priok. Sumber: Kompas
Lantaran itulah langkah Gus Dur tersebut sulit dipahami publik muslim. Di sisi lain kala itu, publik juga telah telanjur menerjemahkan NU merupakan organisasi Islam yang menjadi penentu utama agenda politik “oposisional” politik umat Islam terhadap rezim Orde Baru.
Berbagai sikap keras NU kurun waktu itu membuat Mitsuo Nakamura, pengamat dari Jepang, dalam mengkaji dinamika gerakan sosial politik keagamaan di Indonesia, menjuluki NU sebagai “tradisionalisme-radikal”.
Dalam ulasannya yang berjudul “The Radicalism of the Nahdlatul Ulama in Indonesia” (Southeast Asian Studies II September 1981), Nakamura antara lain menulis, ”NU has emerged as the boldest and most deflate critic of the New Order Government” (NU muncul sebagai kritik yang paling berani dan mengempiskan terhadap pemerintah Orde Baru).
Dalam melihat gejala yang sama, pengamat politik Fachry Ali berkesimpulan, perilaku politik NU pada awal Orde Baru secara tiba-tiba menggantikan posisi Masyumi dalam hal “oposisinya” terhadap negara.
Itu sebabnya Aminudin berpendapat, Gus Dur memiliki perhitungan sendiri, ketika beberapa minggu setelah pembantaian Tanjung Priok, ia mengatur safari Jenderal Moerdani berkeliling ke pondok-pondok pesantren milik NU, terutama di Jawa Timur. “Barangkali langkah itu dirasakan menyengat perasaan pemimpin gerakan Islam lain, namun bagi Gus Dur boleh jadi tindakan ini sebagai upaya mencegah eskalasi kekerasan aparat negara dengan kelompok Islam,” tulis Aminudin.
Tetapi yang jelas, bagi Gus Dur, menurut Aminudin, itu merupakan langkah awal untuk melakukan “koalisi taktis” dengan elit-elit negara terutama Benny Moerdani yang sedang terlibat persaingan politik di antara mereka.

Benny. Sumber: Merdeka
Azas Tunggal
Hal yang mengejutkan lagi, di tengah meluasnya keragu-raguan dan penolakan sebagian umat Islam, NU membuat kejutan dengan menerima asas tunggal paling dahulu, mendahului ormas-ormas Islam lainnya. Lebih jauh, Kiai As’ad Syamsul Arifin malahan menegaskan, menerima Pancasila wajib bagi semua umat Islam dan haram menolaknya, karena sila pertama Pancasila sejalan dengan doktrin tauhid, "tidak ada tuhan selain Allah".
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kenapa NU begitu cepat menyatakan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pertama, terjadinya kemelut internal PPP di sekitar Pemilu 1982 telah merembet ke tubuh NU sehingga masing-masing faksi yang bertikai saling memperebutkan dukungan pemerintah.
Kedua, munculnya tantangan yang meluas di masyarakat terhadap rencana azas tunggal mengakibatkan kelompok mana yang lebih dulu menerima memiliki bobot politis yang besar, ini berarti merupakan kesempatan gerakan “pemikiran baru” di NU untuk memperoleh kepercayaan kembali negara terhadap NU.
Sekadar catatan saja, berbagai perkembangan di dalam tubuh PPP di seputar pemilu kala itu banyak merugikan NU. Jatah kursi unsur NU banyak dipangkas oleh Ketua Umum PPP, H.J. Naro dan nama-nama tokoh-tokoh andalan NU digeser pada posisi yang tidak mungkin terpilih sebagai anggota DPR.
Dalam berbagai peristiwa yang merugikan NU itu, Presiden Partai Idham Chalid nyaris tidak bisa berbuat banyak, dan anehnya, faksi NU dari kelompok Idham hampir tidak ada yang tersingkir dalam daftar urut jadi.
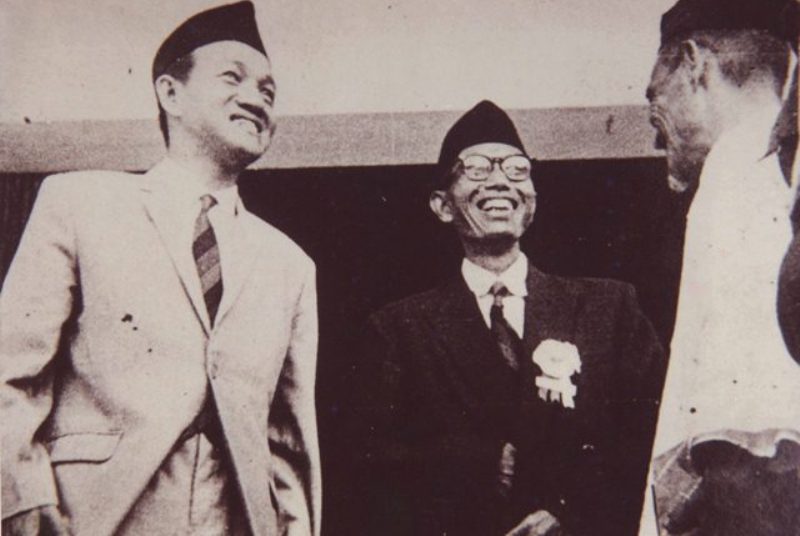
Idham Chalid. Sumber: NU Online
Bersamaan dengan itu, para anggota generasi muda NU yang lebih berpendidikan merasa bahwa Idham Chalid sedang membawa NU ke jalan yang buntu. Mereka mengeluhkan kurangnya kemampuan Idham berpikir jangka panjang, dan merasa bahwa NU sangat memerlukan seorang pemimpin yang memiliki visi masa depan yang lebih kental. Dengan demikian, kekecewaan terhadap kepemimpinan Idham menjadi semakin terakumulasi di kalangan NU, terutama kaum muda yang berhaluan “pemikiran baru”.
Berbagai perkembangan NU yang mulai memprihatinkan telah mendorong beberapa anggotanya untuk melakukan gerakan perubahan di tubuh organisasi Islam terbesar itu. Gagasan-gagasan agar NU meninggalkan gelanggang politik partisan dan perubahan kepemimpinan NU semakin mendapat dukungan yang luas, terutama dari tokoh-tokoh muda NU dan ulama-ulama Jawa Timur.
Dalam sebuah pertemuan ulama-ulama terkemuka NU di Surabaya l Mei 1982, disepakati untuk mengaktifkan kembali K.H. Idham Chalid sebagai top leader NU. Apabila kesehatannya tidak lagi memungkinkan sebaiknya diminta untuk mundur dari jabatannya.
Kudeta
Forum juga mengamanatkan pada tiga ulama terkemuka NU, antara lain Kiai As’ad Syamsul Arifin, Kiai Machrus Ali, dan Kiai Ali Maksum, untuk menemui Kiai Idham Chalid di Jakarta. Keesokan harinya tiga kyai tersebut, bersama dengan Kiai Masjkur, menemui Idham dan melakukan persuasi untuk mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
Di situ lantas disusun konsep pengunduran diri Kiai Idham Chalid dari jabatan Ketua Umum Tanfidziyah PB-NU. Inisiatif atas “kudeta” ini nampaknya datang dari Kiai As’ad, tetapi banyak yang menduga, para “pembaru muda" 78 seperti Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifuddin, dan teman-temannya, sebagai penggerak di balik layar.
Terjadinya “kudeta” internal terhadap Idham cukup mengejutkan bagi kebanyakan warga NU, dan situasi ini menjadi lebih membingungkan lagi ketika sepuluh hari kemudian Idham menarik kembali pernyataan pengunduran dirinya.
Semenjak itu, NU terbelah menjadi dua kubu, yang kemudian dikenal sebagai kelompok Cipete (faksi Idham) dan kelompok Situbondo (faksi Abdurrahman Wahid dan Kiai Ali Maksum). Nama kelompok Situbondo mencerminkan semakin menonjolnya pengaruh Kiai As’ad Syamsul Arifln.
Sejak saat itu penguasa memperlakukan Kiai As’ad sebagai ulama pemuka NU, yang memperkuat posisinya di dalam organisasi ini, terutama di kalangan mereka yang ingin memperbaiki hubungannya dengan pemerintah. Tampaknya, menurut Martin Van Bruinessen, dalam buku Tradisi Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wanaca Baru (1994) para pembaru muda NU juga secara sengaja berusaha mengukuhkan prestise Kiai A's’ad, dengan maksud menggunakannya untuk melegitimasi naiknya mereka ke posisi puncak.
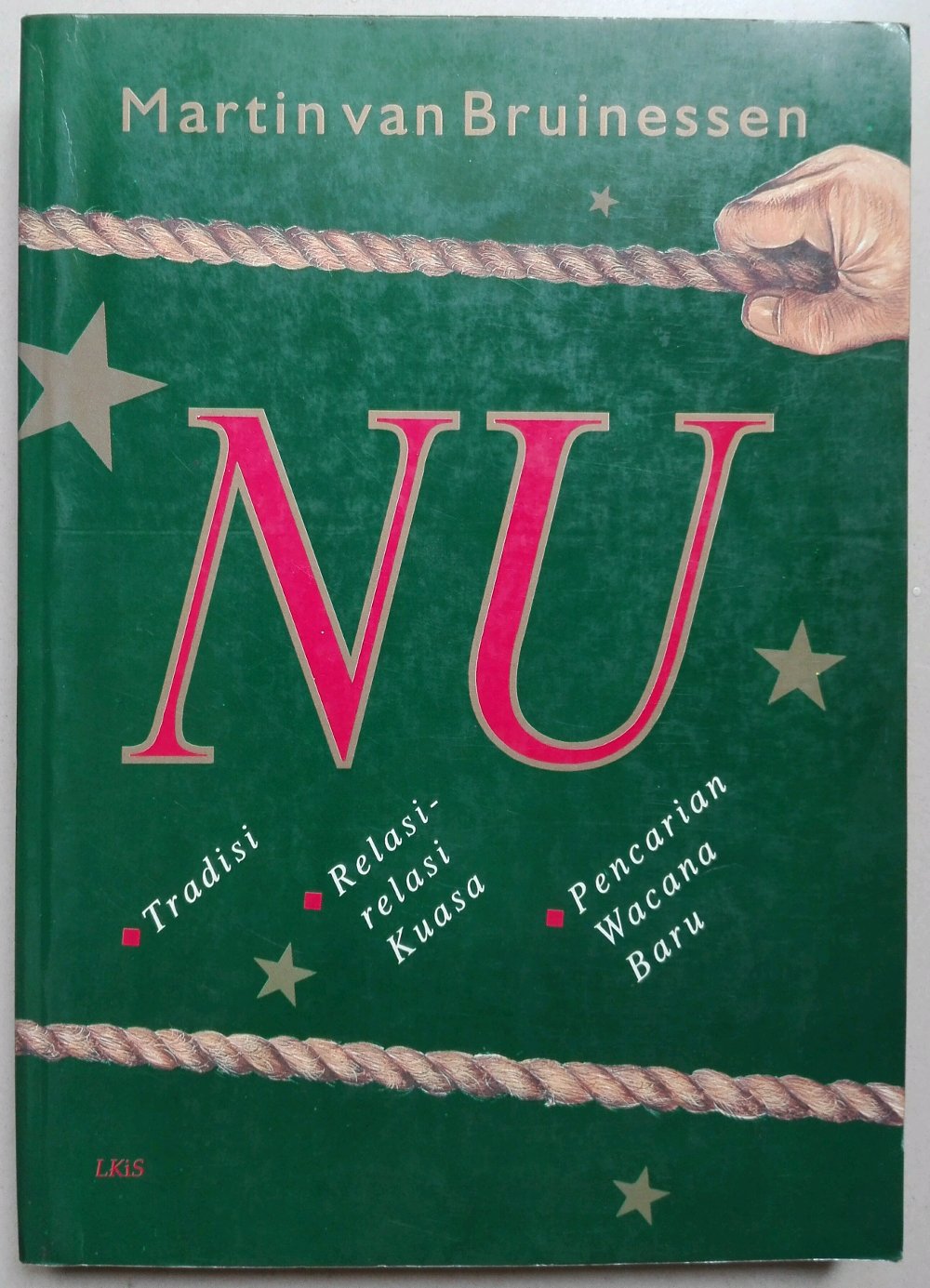
NU-Martin. Sumber: Bukalapak
Kedua faksi yang terlibat persaingan sama-sama berusaha memperlihatkan sebagai kelompok yang mendapat dukungan dari negara dan dari kalangan NU sendiri. Untuk memperoleh pengakuan dari negara, tentu saja, kelompok yang diprioritaskan adalah mereka yang lebih akomodatif terhadap negara, terutama mengangkat persoalan asas tunggal Pancasila.
Dalam konteks semacam inilah proses percepatan NU menerima asas tunggal Pancasila bisa dimengerti. Meskipun dari kedua kubu yang bersaing sama-sama menyatakan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, negara agaknya lebih condong ke kubu Situbondo.
Keberpihakan negara terhadap kubu Situbondo disebabkan kubu ini terdapat “pemain-pemain baru” yang relatif tidak terlibat langsung gaya politik “oposisional” NU di parlemen, selain kelompok ini juga telah merintis akses lobi yang kuat dengan pejabat-pejabat penting negara. Atas dasar itu, rezim Orde Baru memperkirakan kelompok ini lebih bisa menuruti kepentingan pemerintah, atau setidaknya lebih kompromistis dibandingkan NU di bawah kepemimpinan Kiai Idham Chalid.
Khittah 1926
Diselenggarakannya Munas NU di Situbondo menandai kemenangan penting “pembaru muda”. Munas yang diselenggarakan di Situbondo, Jawa Timur, ini berhasil mengambil keputusan strategis menyangkut kembalinya NU sebagai organisasi sosial secara penuh yang berarti melepaskan dirinya secara organisatoris dengan partai politik (PPP).
Kemudian langkah perubahan dikenal sebagai kembali ke khittah 1926. Materi pemulihan khittah 1926 sebenarnya telah lama digodok, dan yang terakhir dirumuskan oleh tim tujuh yang dipelopori “pembaru muda” Abdurrahman Wahid dan Fahmi Saifuddin.
Menurut Kacung Marijan dalam buku Quo Vadis NU? (1992), semua yang terlibat dalam tim tujuh ini merupakan “generasi ketiga” yang terdiri dari intelektual muda NU, yang tidak hanya bersentuhan dengan nilai-nilai pesantren, tetapi juga nilai-nilai lain yang kosmopolit sifatnya.

Quo Vadis NU. Sumber: Bukalapak
Pada dasawarsa 1970-an, mereka, sendiri-sendiri atau bersama kelompok lain, secara intensif melakukan pencarian model pembangunan yang diilhami etika sosial Islam. Pada mulanya mereka bergerak sendiri-sendiri lewat profesinya masing-masing, setelah itu mereka sering bertemu.
Kalangan “pembaru muda” tersebut, di penghujung 1970-an, sering melakukan sharing pemikiran di antara mereka dan semakin intensif melakukan refleksi kritis terhadap sebab-sebab kemunduran NU. Dari sini mereka melihat perlunya segera dilakukan suatu terobosan dengan meyakinkan tokoh-tokoh NU bahwa kembali ke khittah 1926 merupakan suatu keharusan. “Cara yang dilakukan adalah lewat silaturahmi ke para kiai dan menerbitkan jurnal khittah,” tulis Kacung.
Akhirnya, suatu teks yang menegaskan bahwa NU kembali ke khittah 1926 berhasil disepakati dalam Munas Situbondo. Kalimat awalnya, bahwa “Nahdlatul Ulama adalah Jami’iyah Diniyah Islamiyah ...” Alinea dalam teks keputusan yang menyangkut hubungan NU dengan politik itu berbunyi:
“Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota NU. Tetapi NU bukan merupakan wadah kegiatan politik praktis. Penggunaan hak berpolitik dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada dan dilaksanakan dengan akhlaqul karimah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tercipta kebudayaan politik yang sehat. NU menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik, bersungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.”
Kemudian, dengan diselenggarakannya Muktamar ke-27 pada 1984, diselenggarakan juga di Situbondo, posisi “pembaru muda” semakin menguat. Keputusan-keputusan politik penting yang diambil dalam muktamar itu lebih banyak bersifat mempertegas hasil Munas yang diadakan sebelumnya.
Gus Dur yang dijagokan kubu Situbondo dengan mudah meraih jabatan Ketua Umum Tanfiziyah PB-NU yang baru karena Cholid Mawardi, calon yang diunggulkan kubu Cipete, “didubeskan” pemerintah ke Syria beberapa bulan sebelum muktamar.
Menurut Martin, komposisi pengurus memperlihatkan kelompok “pembaru muda” banyak memegang posisi kunci dalam kepengurusan PB-NU baru ini. Dengan hasil semacam ini semakin memperkokoh NU dalam merambah jalan baru, artikulasi politik tanpa “partai Islam”.
