Ceknricek.com -- Mendung memayungi dunia sastra Indonesia ketika seorang penerjemah ulung yang mumpuni di bidangnya, mengembuskan nafas terakhir tepat pada tanggal hari ini, tiga tahun lalu, 20 Juni 2016. Ia adalah Ali Audah. Semasa hidup, almarhum telah menerjemahkan berbagai karya dunia untuk pembaca di Indonesia.
Ali Audah, seorang penerjemah yang dikenal dengan spesialisasinya menerjemahkan karya-karya sastra Timur Tengah, sekaligus penulis konkordasi Al-Quran. Sumbangsihnya untuk ladang kebudayaan Indonesia tentunya tidak dapat dilupakan, bahkan hingga hari ini.
Tidak Makan Sekolahan
Suatu hari, tahun 1930-an, pada zaman kolonlisme Belanda masih mengangkangi bumi Nusantara, di Bondowoso Jawa Timur, seorang anak kecil berusia 6 tahun bolos sekolah. Ia lalu asyik bermain gundu bersama teman-temannya sambil mencoret-coret tanah hingga sesekali menggumamkan huruf-huruf latin.
Lain waktu, pada saat musim angin pasang di sore hari, ia akan pergi ke sawah sambil menyeruti batang bambu untuk dibuat layang-layang. Ketika keringat di bajunya lengket di badan, ia akan segera mandi di kali tak jauh dari sawah tersebut.
Lelaki berperawakan sedang dengan tahi lalat di dagunya itu Ali Audah kecil. Ia lahir dari pasutri Salim Audah dan Aisyah Jubran pada 14 Juli 1924. Ali lecil memang terkenal bandel. Ia bahkan pernah dikerangkeng, dan sering membolos sekolah sampai di hari tuanya.

ali-audah. Sumber: Islami.co
Mungkin tidak berpikir bahwa ‘kebengalannya’ yang diimbangi dengan melahap berbagai macam bacaan, membuatnya jatuh cinta pada kata-kata dan memilih hidup menjadi penerjemah.
“Saya baca apa saja, mulai dari kertas koran pembungkus kue atau gula pasir, sampai majalah bekas dan buku-buku pelajaran atau bacaan anak-anak sekolah kawan sepermainan,” tuturnya.
Membaca riwayat hidup dari penerjemah ‘Lorong Midaq’ karya peraih nobel sastra Naguib Mahfouz ini, pembaca memang bisa mengeleng-gelengkan kepala. Bagaimana tidak, tamat Ibtidaiyah pun tidak, namun ia mampu menguasai berbagai bahasa asing dan menjadi pembantu rektor sebuah perguruan tinggi.
Dari tangannya yang dingin lahir banyak terjemahan yang bernas, seperti: Sejarah Hidup Muhammad, karya Muhammad Husain Haikal; Abu Bakar as-Siddiq, Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi, dan masih banyak lagi. Namun yang menjadi masterpiece-nya tentu saja; Konkordansi Qur’an, Panduan Kata dalam Mencari Ayat Qur’an yang sangat bermanfaat bagi orang awam.

Sumber: Khittah.co
Jatuh Cinta Pada Sastra
Ali mengaku lupa mengapa ia tertarik dan jatuh cinta kepada karya sastra. Yang dia ingat bacaan yang pertama kali dibaca antara lain karya pengarang Merajoe Soekma dari Banjarmasin. Di usia remaja, di Bondowoso, Jawa Timur, mula-mula ia gemar melukis. Belakangan menulis puisi dan naskah drama.
Pada tahun 1940-an, ia mendapat hadiah pertama dan kedua dalam lomba menulis puisi dan drama se-Jawa Timur. Dan untuk pertama kali, puisinya dimuat di majalah Sastrawan, Malang, di awal revolusi. Karena tertarik pada karya-karya pengarang Muhammad Dimjati, ia pun berusaha mencari dan berkenalan dengan wartawan dan sastrawan yang cukup terkenal di tahun 1950-an itu di Solo.
“Saya banyak belajar dan mendapat dorongan semangat dari Pak Dim yang tinggal di sebuah rumah sederhana di perkampungan batik di Laweyan,” tuturnya lagi. Ia pun lantas menetap di Solo. Namun, barangkali lantaran mendambakan suasana tenang dan sejuk untuk menulis, maka di awal 1950-an ia pindah ke Bogor, Jawa Barat.
Di sanalah Ali Audah sampai akhir hayatnya hanya hidup dari menulis, dan “berkantor” di rumahnya. Sejak itu, dari tangannya meluncur sejumlah karya berupa cerita pendek, esai, kritik sastra, beberapa artikel mengenai berbagai masalah kebudayaan dan kesenian. Ia juga menerjemahkan karya-karya sastra dan buku-buku agama karya para sastrawan dan penulis terkenal sebagaiaman dikemukakan di atas.
Sapardi, menuliskan di majalah Tempo, sosok Ali Audah sebagai orang yang diam dan tidak berapi-api.

Sapardi dan Ali Audah. Sumber: Copyvisual
"Ia bukan pribadi yang membuat repot karena 'bahasa'-nya sulit, tapi 'menerjemahkan'-nya ke dalam sebuah tulisan ringkas tidak mudah saya lakukan. Pak Ali--begitu saya memanggilnya--menunjukkan sikap yang tidak pernah berlebihan: cara bicaranya, gerak-geriknya, tatapan matanya, dan pokok pembicaraannya tidak menimbulkan rasa kikuk.”
Ali Audah Berbicara Terjemahan
Bagi Ali Audah, terjemahan yang baik adalah yang tengah-tengah tanpa mengurangi gaya asli pengarang. Artinya, tidak verbatim atau harfiah, juga tidak parafrase atau terlalu bebas. Lebih baik lagi jika gaya si pengarang bisa diambil.

Arsip Ali Audah. Sumber: Warung Arsip
Namun, bagi sebagian orang yang tak paham, pengambilan gaya si pengarang kerap dianggap harfiah alias terjemahan plek. Lebih lanjut ia menerangkan, terjemahan verbatim atau harfiah adalah jenis terjemahan yang buruk karena kerap menghamparkan teks yang justru sulit bahkan tidak dapat dimengerti.
Sementara terjemahan parafrase adalah bentuk ketidakberdayaan penerjemah. Karena menurutnya, si penerjemah tidak bisa menangkap pikiran sang pengarang, tidak bisa menangkap bahasanya, sehingga si penerjemah menuliskan pikirannya sendiri.
“Kalau terjemahan itu (kita) cocokkan dengan aslinya, tidak bisa dilacak. Penerjemah bikin kalimat sendiri, paragraf sendiri, dan seterusnya. Ini sangat berbahaya, karena konsep, pikiran dan gaya--bahkan nuansa pikiran pengarang--tidak bisa ditangkap dan diungkapkan,” terangnya, dikutip dari catatan wartawan Tempo, Budiman S. Hartoyo.

Sumber: Tempo
Kepada penerjemah yang mengalami kesulitan seperti itu, Ali Audah mewanti-wanti untuk berhati-hati agar tidak menambal terjemahannya dengan kalimat bikinannya sendiri, karena hal itu bisa sangat berbahaya, hingga mengakibatkan nuansa pikiran pengarang tidak bisa diungkapkan.
Lebih lanjut ia meyarankan untuk mengatasinya dengan catatan kaki, misalnya begini. “Kalimat atau alinea yang ini sulit diterjemahkan, dan inilah terjemahan yang paling mendekati.”
Seorang penerjemah, menurut Ali, juga tidak bisa menerjemahkan karya ilmiah atau agama hanya dengan mengandalkan ensiklopedia atau kamus. Ia juga harus menggunakan buku-buku referensi. Kalau tidak, ia khawatir terjemahan itu meleset.
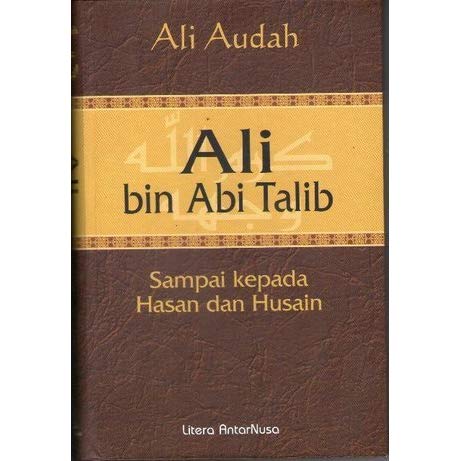
Ali-AliAudah. Sumber: Goodreads
“Untuk menerjemahkan buku sejarah, dia harus membaca pula buku sejarah karya pengarang lain. Kalau menerjemahkan buku biografi, ia harus membaca biografi lain. Dia tidak bisa ingin cepat-cepat selesai menerjemahkan hingga terburu-buru. Sedang untuk menerjemahkan novel, harus dilihat pula latar belakang budayanya,” tutupnya.
Akhir Hayat Sang Penerjemah
Sembilan tahun setelah Budiman S. Hartoyo melakukan wawancara dengan Ali Audah, pada tanggal hari ini, 20 Juni 2016, ia "menerjemahkan" diri dan nasib di guratan-guratan tangannya. Ali, sastrawan dan penerjemah karya sastra itu wafat dalam usia 93 tahun, di rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat.
Dunia sastra Indonesia kehilangan sakah seorang tokoh terbaiknya.
“Hari ini kita bersama-sama menundukkan wajah dan membungkukkan badan di hadapan beliau Bapak Ali Audah. Saya pribadi, kalau boleh jujur mempraktikkannya, tidak akan menundukkan wajah, melainkan menutupi wajah, karena rasa malu yang mendalam kepada beliau. Saya juga tidak akan membungkukkan badan, melainkan melarikan diri dan bersembunyi, karena rasa tak berharga di hadapan beliau," ungkap Budayawan Emha Ainun Nadjib di dalam salah satu esainya.
Meski terkesan mengglorifikasi, tapi kiranya ungkapan Emha itu sah-sah saja dialamatkan kepada Ali Audah yang sepanjang hayatnya “mengimani” terjemahan sebagai sebuah pokok yang rumit. Almarhum mengerjakannya sepenuh dedikasi untuk pembaca karya sastra di Indonesia.
