Ceknricek -- Bagi Al Farabi ilmu dalam segala wujud sebagaimana daya dan upayanya untuk menuju sains akan sampai kepada sesuatu yang mirip dengan ajaran ketuhanan. Sains yang satu, sains yang mencakup segala hal dan menggambarkan dunia kepada manusia sebagai semesta.
Abu Nasir Muhammad bin Al-Farakh Al-Farabi disingkat Al-Farabi (870-950 M), dikenal di dunia Barat sebagai Alpharabius adalah seorang ilmuan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia dianggap sebagai filsuf Islam pertama yang secara sungguh-sungguh mengkaji filasafat Yunani klasik.
Kemampuan Al Farabi dalam memahami, menjabarkan, serta mengkomparasikan filsafat Yunani klasik Plato dan Aristoteles dengan filsafat Islam membentuk reputasinya sebagai salah satu filsuf kaliber dunia. Dari sanalah ia akhirnya mendapat julukan terhormat: The Second Master atau Guru Kedua setelah Aristoteles.

Al Farabi Second Teacher. Sumber : Alshindagah
Ada cerita menarik yang menjadi salah satu alasan Al Farabi dikenal di dunia Timur sebagai Aristoles kedua tersebut. Syahdan, Ibnu Sina hendak mempelajari buku Metafisika karya Aristoteles. Berulangkali ia membaca buku itu, bahkan ia nyaris hafal isinya, namun ia tak kunjung memahaminya. Secara tidak sengaja, Sina kemudian menemukan buku Fi Aghradh Kitabi ma ba’da ath-Thabi’ah li Aristhu karya Al-Farabi. Melalui buku itu barulah Sina memahami uraian-uraian Aristoteles dalam Metafisika.
“.. Tatkala hendak mempelajari ilmu ketuhanan al-‘ilm al-Ilahi, dan berusaha membaca buku Ma ba’da ath-Thabi’ah karya Aristoteles, saya tidak dapat memahaminya, bahkan saya samar terhadap maksud dari penulisan buku itu…” kata Sina dilansir dari M. Hadi Masruri dalam Ibn Thufail.
Dalam filsafatnya, Al-Farabi sering menggabungkan antara filsafat Aristoteles, Plato, dan Neoplatonisme dengan pemikiran Islam bermazhab Syiah Imamiyah. Aristoteles memengaruhinya dalam hal logika dan fisika. Plato memengaruhinya dalam pemikiran ahlak dan politik. Sedangkan dalam masalah metafisika ia dipengaruhi oleh Plotinus.
Pemikiran Alfarabi tentang Negara
Filsafat Al Farabi tentang negara banyak dipengaruhi oleh Plato, Aristoteles, dan Ibnu Rabi. Pada intinya Al Farabi berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan bermasyarakat. Hal ini karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama pihak lain.
Dalam uraiannya di kitab Al-Madinah Al Fadhilah (Kota atau Negara Utama), menjelaskan masyarakat ibarat tubuh manusia, jika salah satu organ sakit maka bagian tubuh lain akan merasakan sakit. Oleh karena itu setiap individu di masyarakat harus mendapat bagian pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Pembagian tugas individu sangat ditentukan oleh kepala negara. Ibarat jantung dalam tubuh manusia, kepala negara menjadi sumber aktivitas, peraturan, teladan, informasi, dan petunjuk agama masyarakat. Maka dari itu, menurut Al-Farabi, negara yang baik adalah seperti orang yang sehat karena pertumbuhan dan perkembangannya teratur di antara satu unsur dengan unsur lainnya. Sedangkan negara yang bangkrut adalah ibarat orang sakit karena kurang pertumbuhan dan perkembangan yang teratur.

Sumber : radiounisia.com
Al Farabi percaya tujuan manusia bermasyarakat adalah untuk meraih kebahagiaan tertinggi. Yakni kebahagiaan yang tidak saja bersifat materiil (duniawi) tetapi juga spiritual (ukhrawi). Menurutnya ada setidaknya tiga tipologi manusia yang berhak menjadi kepala negara dan memimpin sebuah negeri. Mereka ialah filsuf, raja dan nabi. Ketiganya dianggap Al-Farabi sebagai orang pilihan.
Filsuf menurut Al-Farabi ialah mereka yang tidak saja memiliki intelektualitas teori tapi praksis, rasional, dan kritis. Pandangan ini agaknya dipengaruhi oleh Plato yang menganggap masyarakat ideal adalah masyarakat yang dipimpin filsuf. Sebab filsuf mengerti makna hidup serta memahami hal-hal yang baik dan buruk. Masyarakat awam mungkin bisa membedakan baik dan buruk tetapi mereka tidak sekritis filsuf. Sehingga kepemimpinan masyarakat ataupun negara, menurut Plato, sebaiknya diserahkan kepada filsuf.
Tipologi pemimpin kedua menurut Al-Farabi adalah raja yang memiliki garis keturunan penguasa dan loyalitas tentara. Raja yang menjadi kepala negara juga mesti memiliki ciri-ciri filsuf. Ketiga, tipologi pemimpin negara menurut Al-Farabi ialah nabi. Jika legitimasi kepemimpinan filsuf didapat dari kekuatan penalaran, raja dari kekuatan tentara dan garis keturunan, maka nabi meraih legitimasi kepemimpinan dari moral dan kecintaannya terhadap rakyat.
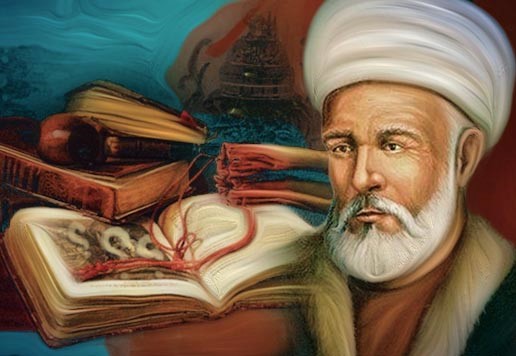
Sumber : tabayyun.dohainstitute.org
Terlepas dari tiga tipologi tersebut, Al-Farabi percaya bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki sejumlah syarat: tidak cacat fisik, memiliki daya pemahaman yang baik, memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, orator yang pandai mengemukakan pendapat dan beretorika, mencintai pendidikan dan pendidik, tidak serakah terhadap makanan, minuman, dan wanita, mencintai kejujuran dan membenci kebohongan, berjiwa besar, tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan dunia, mencintai keadilan dan membenci kezaliman, serta tanggap dan mudah diajak dalam menegakkan keadilan.
Al Farabi dan Musik

Al Farabi Music What More Can I Give. Sumber : sejuknyapagi.wordpress.com
Selain sebagai ilmuwan, Al-Farabi juga dikenal luas sebagai seorang seniman. Ia mahir memainkan alat musik dan menciptakan berbagai instrumen musik. Sistem nada Arab yang diciptakanya hingga kini masih tetap digunakan musik Arab. Al-Farabi juga berhasil menulis buku penting dalam bidang musik yang berjudul, Kitab al-Musiqa.
Sikap Al-Farabi terhadap seni menyerupai sikap Plato, filsuf Yunani klasik yang banyak memengaruhi pemikirannya. Ia menempatkan kesenian dalam konteks sosial-moral. Dalam wacana tentang musik misalnya, Al-Farabi memandang bahwa musik mengandung fungsi untuk mengarahkan jiwa pendengarnya. Dalam hal ini, musik dapat menciptakan perasan tenang dan nyaman.
Musik menurut Al-Farabi juga dapat memengaruhi moral, mengendalikan emosi, mengembangkan spiritualitas, dan menyembuhkan penyakit, seperti gangguan psikomatik. Sehingga bagi Al-Farabi musik bisa menjadi sebuah alat terapi, jika meminjam istilah T.J. De Boer ia menamakannya (the spiritual healing art).
Selain itu, ajaran estetika Al-Farabi tidak bisa dilepaskan dari metafisika. Menurutnya, mata hanyalah kemampuan potensial untuk melihat selama dalam kegelapan, tapi dia menjadi aktual ketika menerima sinar matahari. Bukan hanya obyek-obyek indrawi saja yang bisa dilihat, tapi juga cahaya dan matahari yang menjadi cahaya itu sendiri.
Dalam skema metafisika keindahan berasal dari An-Nur atau cahaya Ilahi. Alam semesta dan benda-benda di dalamnya menjadi indah sejauh berpartisipasi dalam keindahan Ilahi. Secara sederhana, menurut Al-Farabi benda-benda di alam semesta tidaklah indah pada dirinya, tetapi indah karena adanya Tuhan yang menciptakan. Tuhan, menurutnya adalah puncak keindahan tertinggi.
Selama hidupnya, Al-Farabi menulis beberapa karya, antara lain; Al-Jami’u Baina Ra’yani Al-Hkiman Afalatoni Al Hahiy wa Aristho-thails (pertemuan/penggabungan pendapat antara Plato dan Aristoteles). As Suyasatu Al Madinah (politik pemerintahan). Arro’u Ahli Al Madinati Al Fadilah (pemikiran-pemikiran utama pemerintahan), As Syiasyah (ilmu politik). Ihsha’u Al Ulum (kumpulan berbagai ilmu). Al-Madinah Al Fadhilah (Kota atau Negara Utama).
Selain buku-buku tersebut, Al-Farabi juga merangkum berbagai teori keilmuan yang mencakup bahasa, matematika, mantik (logika), fisika politik, hukum, dan ketuhanan ke dalam buku yang berjudul Ihsha’u Al Ulum. Tema-tema tersebut mungkin sudah muncul sebelumnya, tetapi yang membuat buku itu istimewa adalah kemampuan Alfarabi mengawinkan ilmu-ilmu tersebut dengan teori keislaman seperti fiqih (hukum Islam) dan ilmu kalam (aqidah) yang popular masa itu.
Kepribadian dan Akhir Hayat
Selama hidupnya Al-Farabi dikenal sebagai orang yang pendiam dan mengabdikan hidupnya pada filsafat dan kontemplasi. Setelah mendapat pendidikan di Bagdad dari salah satu gurunya, seorang Kristen bernama Yohana Bin Hailan, ia pun menghabiskan masa hidupnya untuk berkarya di Bagdad cukup lama.

Patung Al farabi di Kazakhtan. Sumber : scroll.in
Al-Farabi akhirnya pergi ke Aleppo karena kerusuhan politik. Di sana ia tinggal di istana Saif Al-Daulah yang cemerlang, namun ia memilih untuk menghabiskan akhir hayatnya bukan di istana, melainkan di sebuah tempat pengasingan.
Dalam tunjangan kehidupan istana yang mewah, Al-Farabi memilih untuk hidup zuhud. Abu Ashiba’ah (688 M) berpendapat bahwa al-Farabi tidak pernah mengambil upah dari Saif Daulah kecuali hanya 4 dirham setiap hari hanya untuk kehidupan sehari-harinya.
Menurut T.J De Boer, dalam Sejarah Filsafat dalam Islam (Forum;2019) Al-Farabi meninggal dunia di Damaskus pada bulan Rajab 339 H/ Desember 950 M pada usia 80 tahun dan dimakamkan di luar gerbang kecil (al-bab al-saghir) kota bagian selatan. Konon, sang pangeran sendiri yang memimpin dan menyampaikan pidato pada upacara penguburannya.
