Ceknricek.com -- Reduksi media sosial sebagai semata-mata sarana interaksi sosial membuat publik cenderung mengabaikan tanggung jawab perusahaan (platform) media-sosial sebagai entitas bisnis. Jika ada hoaks yang meresahkan masyarakat, masalahnya dilokalisir sekadar sebagai masalah antara pembuat, korban, dan pembaca hoaks. Perusahaan media sosial yang memperantarai penyebaran hoaks seperti memperoleh impunitas. Mereka tidak dituntut untuk memikul tanggung jawab. Padahal logikanya, semakin kontroversial hoaks, semakin populer platform media sosial yang menyebarkannya. Popularitas ini kemudian berkorelasi dengan kenaikan nilai saham perusahaan pemilik platform berikut potensi pendapatan iklannya. Semakin banyak pengguna media sosial, semakin banyak pula data perilaku pengguna internet (internet user behavior) yang berhasil ditambang untuk kebutuhan pengembangan kecerdasan buatan dan machine learning.
Impunitas perusahaan media sosial itulah yang menonjol dalam kontroversi tentang gelombang hoaks yang meresahkan masyarakat setelah pengumuman hasil Pilpres 2019. Perbincangan publik hanya mempersoalkan siapa yang membuat hoaks, siapa sasarannya, bagaimana reaksi masyarakat, serta apa tindakan pemerintah dan polisi untuk menanganinya. Bagaimana posisi perusahaan media sosial yang turut menyebarkan hoaks yang mengharu-biru perasaan masyarakat itu? Luput dari pergunjingan publik.
Tampak jelas di sini kesenjangan penanganan hoaks di Indonesia dan di Eropa, atau Australia. Dalam perspektif Eropa atau Amerika Serikat, beban tanggung jawab atas penyebaran hoaks melalui media sosial--terutama bukan hanya pada si pembuat hoaks--melainkan juga pada perusahaan media sosial. Perusahaan inilah yang menciptakan dan mengembangkan platform media sosial. Platform media sosial inilah yang memperantarai persebaran hoaks dan memetik keuntungan dari besarnya perhatian publik atas hoaks tersebut. Oleh karena itu, fokus penanganan hoaks tidak hanya pada si pembuat hoaks, tetapi terutama sekali pada perusahaan pemilik platform media sosial.
Mengapa tanggung jawab perusahaan media sosial luput dari perhatian di Indonesia? Karena kita umumnya tidak memperhitungkan media sosial sebagai entitas bisnis yang berorientasi ekonomi. Kata sosial dalam istilah media sosial sedemikian rupa menghegemoni kesadaran publik. Kita terlambat menyadari, yang sedang kita hadapi bukan hanya entitas sosial yang secara cuma-cuma memfasilitasi masyarakat untuk berinteraksi sosial dengan cara yang baru, melainkan juga entitas bisnis yang motif utamanya adalah instrumentalisasi dan komodifikasi. Para pengguna media sosial sesungguhnya adalah “instrumen” bagi perusahaan platform untuk menambang data perilaku sebanyak-banyaknya sekaligus sasaran dari iklan digital tertarget yang dalam prakteknya sedemikian jauh menerabas privasi para pengguna media sosial.
Dalam konteks inilah tuntutan agar perusahaan media sosial lebih bertanggungjawab secara hukum menguat belakangan. Bagaimana dan sejauh mana tanggung jawab itu mesti dirumuskan?
Pertama, seperti diusulkan The Cairncross Review (2019), perusahaan media sosial bertanggungjawab mendidik penggunanya untuk mengidentifikasi asal, kualitas, dan tingkat kepercayaan informasi media sosial. Masyarakat perlu diajari bagaimana menyeleksi, menilai, dan mempertimbangkan konten yang tersebar melalui platform media sosial. Dalam kaitan ini, menjalankan literasi media bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab perusahaan media sosial.
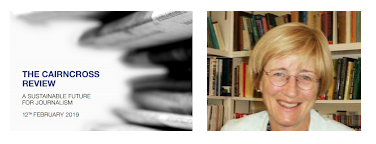
Sumber: Istimewa
Mereka yang mengambil keuntungan terbesar dari ketergantungan masyarakat terhadap media-sosial sehingga semestinya mereka juga berperan lebih nyata untuk menghindarkan masyarakat dari dampak buruk media sosial. Pertimbangan lain, perusahaan media sosial yang paling memahami bagaimana platform media sosial bekerja dan berinteraksi dengan penggunanya. Mereka pula yang mengetahui hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun daya tahan pengguna menghadapi terpaan hoaks dan disinformasi.
Kedua, beberapa pihak mengusulkan perusahaan media sosial diwajibkan memoderasi konten yang terdistribusikan melalui platform yang mereka kelola. Mereka harus menyunting konten yang merugikan publik atau melanggar undang-undang. Namun, langkah preventif ini--menurut Cairncross Review--kurang mempertimbangkan perbedaan posisi perusahaan media sosial sebagai distributor konten dan pengguna media sosial sebagai pembuat konten.
Selain itu, secara teknis sulit membayangkan platform media sosial harus memeriksa jutaan konten buatan pengguna setiap sehari. Memberikan kendali yang kuat kepada perusahaan media sosial untuk mengontrol konten juga dianggap sebagai pilihan yang berisiko. Perusahaan media sosial dapat secara ketat menyensor konten yang menyebar melalui platform mereka untuk menghindari sanksi seperti telah terjadi dalam penerapan The Network Enforcement Act (NetzDG) di Jerman.

Sumber: medium.com
Ketiga, jika langkah preventif tadi sulit dilakukan, perusahaan media sosial bertanggungjawab untuk sesegera mungkin menghapus konten yang merugikan masyarakat atau melanggar hukum. Hal inilah yang diatur di Jerman dengan NetzDG dan di Australia dengan The Sharing of Abhorrent Violent Material Bill 2019. Dalam dua undang-undang ini, perusahaan media sosial wajib membangun sistem deteksi penyebaran hoaks pada platform masing-masing secara proaktif maupun atas dasar pengaduan masyarakat. Begitu konten tersebut terdeteksi, perusahaan platform harus segera meresponnya yang mengarah pada tindakan penghapusan konten. Kelalaian dalam mengambil langkah kuratif ini melahirkan sanksi denda yang berat.
NetzDG memberikan batas waktu 24 jam atau tujuh hari--untuk kasus yang kompleks--kepada perusahaan media sosial yang beroperasi di Jerman dan memiliki pengguna lebih dari dua juta orang untuk menyelidiki, dan menghapus konten ilegal pada platform mereka setelah menerima pengaduan. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, pemerintah Jerman menerapkan denda hingga US$60 juta atau setara dengan Rp805 miliar kepada perusahaan media sosial. Dalam kasus Australia, The Sharing of Abhorrent Violent Material Bill menerapkan denda kepada perusahaan media sosial sebesar 10 persen dari pendapatan tahunan global perusahaan tersebut, jika mereka terbukti tidak segera menghapus konten kekerasan pada platform media sosial mereka. Atas kesalahan yang sama, para eksekutif perusahaan itu juga terancam hukuman hingga tiga tahun penjara. Materi kekerasan yang dimaksud merujuk pada video yang bermuatan pembunuhan, perusakan, terorisme, penyiksaan, atau pemerkosaan.
Muncul kekhawatiran akan dampak yang merugikan dari skema tanggung jawab yang seperti ini. Perusahaan media sosial dikhawatirkan akan secara ketat menyensor konten buatan pengguna. Seperti telah disinggung, hal ini untuk menghindari hukuman denda yang diterapkan undang-undang. Persoalan lain, seringkali tidak cukup jelas definisi hoaks, konten berbahaya, atau konten merugikan yang mendasari penghapusan konten. Jangan-jangan mengkritik pemerintah juga dianggap hoaks? Muncul potensi pelanggaran prinsip kebebasan berpendapat atau berekspresi di sini. Apalagi belum diatur secara memadai mekanisme banding atas keputusan penghapusan konten yang dilakukan perusahaan media sosial dengan alasan-alasan di atas. Jangan-jangan terdorong oleh ketakutan terhadap sanksi denda, perusahaan media sosial melakukan sensor secara serampangan?
Kejelasan definisi dan parameter tentang konten media sosial yang melanggar hukum atau merugikan kepentingan publik, serta tersedianya mekanisme banding atas keputusan penghapusan konten oleh perusahaan media sosial atau pemerintah perlu ditegaskan jika Indonesia ingin mengadopsi NetzDG Jerman. Hal yang tak kalah penting adalah menghindari sentralisasi pengelolaan konten kepada pemerintah atau perusahaan media sosial.
Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga perwakilan publik sebagai regulator pengelolaan konten media sosial. Pengaturan media sosial sebagai ruang publik baru tidak diserahkan kepada industri atau pemerintah, tetapi kepada lembaga perwakilan publik yang mampu menjaga jarak dari tendensi pengendalian dan penguasaan. Sesuatu yang sangat potensial datang dari arah industri maupun pemerintah.

Gedung legislatif. Sumber: ngopibareng.id
Lembaga perwakilan publik itu berfungsi: (1) melakukan pengawasan atas kinerja platform media sosial dalam mengendalikan konten media sosial; (2) merumuskan definisi dan parameter konten media sosial yang melanggar hukum atau merugikan kepentingan publik dengan berpegang pada prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi; (3) menyusun standar pengawasan dan pengendalian konten media sosial; (4) memastikan proses penghapusan konten media sosial dilaksanakan secara hati-hati, berdasarkan parameter yang jelas dan mekanisme yang transparan; (5) menjembatani kepentingan perusahaan media sosial, pemerintah, dan masyarakat; (6) merumuskan mekanisme banding atas penghapusan konten media sosial; (7) memutuskan sanksi untuk perusahaan media sosial atas penyebaran konten yang melanggar hukum atau merugikan kepentingan publik.
Agus Sudibyo, Head of New Media Research Center ATVI Jakarta
